
Tri Sulistianing Asuti contributed to the Book Mengarungi Jejak Merajut Asa: 75 Tahun Indonesia-Tiongkok published by IRCiSod (2025). Tri wrote about “Wajah Baru Istiqlal: China Space dan Diplomasi Toleransi Beragama.”


Tri Sulistianing Asuti contributed to the Book Mengarungi Jejak Merajut Asa: 75 Tahun Indonesia-Tiongkok published by IRCiSod (2025). Tri wrote about “Wajah Baru Istiqlal: China Space dan Diplomasi Toleransi Beragama.”

Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono presented a comprehensive report on Indonesia in the fifth edition of The International Review of Constitutional Reform. This report provides a comprehensive analysis of significant constitutional developments and reforms that have impacted the nation’s governance.
The International Review of Constitutional Reform (IRCR) is a first-of-its-kind scholarly effort to gather jurisdictional reports–written by scholars and judges, often in collaboration–on all forms of constitutional revision around the world over the past year.
Suggested Citation:
Barroso, Luis Roberto and Albert, Richard, The 2024 International Review of Constitutional Reform (November 05, 2025). Published by the Constitutional Studies Program at the University of Texas at Austin in collaboration with the International Forum on the Future of Constitutionalism 2024 (ISBN: 978-1-7374527-8-2); U of Texas Law, Legal Studies Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5706743 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5706743
Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Eddyono presented their paper “Polygamy and How the Indonesian Constitution Court Interpreted the Koran” in the International Conference on Scripture for Peace and Humanity: Scriptural Reasoning, Contextualist Approach, and Social Reception.
The International Conference on Scripture for Peace and Humanity was an event held in Yogyakarta, Indonesia, on June 20-21, 2023, focusing on how scripture is interpreted for peace or conflict. The conference aimed to bring together scholars from various religious traditions to examine the role of scriptural reasoning and contextualist approaches in promoting tolerance or intolerance. It also explored the social reception and impact of different scriptural interpretations.



Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono made report about Indonesia on the 3rd edition of The International Review of Constitutional Reform (ISBN: 978-1-7374527-4-4).
The International Review of Constitutional Reform (IRCR) is a first-of-its-kind scholarly effort to gather jurisdictional reports–written by scholars and judges, often in collaboration–on all forms of constitutional revision around the world over the past year.
This edition contains over 80 jurisdictional reports. Each report explains and contextualizes events in constitutional reform over the previous year in a given jurisdiction. Constitutional reform is defined broadly to include constitutional amendment, constitutional dismemberment, constitutional mutation, constitutional replacement and other events in constitutional reform, including the judicial review of constitutional amendments.

This is the 4th edition of The International Review of Constitutional Reform (ISBN: 978-1-7374527-6-8).
The International Review of Constitutional Reform (IRCR) is a first-of-its-kind scholarly effort to gather jurisdictional reports–written by scholars and judges, often in collaboration–on all forms of constitutional revision around the world over the past year.
This edition contains 90 jurisdictional reports. Each report explains and contextualizes events in constitutional reform over the previous year in a given jurisdiction. Constitutional reform is defined broadly to include constitutional amendment, constitutional dismemberment, constitutional mutation, constitutional replacement and other events in constitutional reform, including the judicial review of constitutional amendments.
Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono made report from Indonesia.



Luthfi Widagdo Eddyono contributed to the Secretariat for Research and Development (SRD) of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) for its seventh research book, entitled “Constitutional Rights and the Environment.”


Luthfi Widagdo Eddyono contributed to the Secretariat for Research and Development (SRD) of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) for its sixth research book, titled “Access to Justice: Constitutional Perspectives.” He and other writers explored the intricate ways constitutional frameworks influence access to justice, covering different aspects of current issues like digitalization and the impact of the recent COVID-19 pandemic.


Tri Sulistianing Astuti menulis “Parliamentary Threshold dan Fragmentasi Parlemen” di Majalah Konstitusi, edisi November 2024. Tulisan tersebut mengetengahkan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, yaitu Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menentukan, berkenaan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagaimana ditentukan
norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan.
Tri mengungkapkan: “Pada prinsipnya, pemberlakuan parliamentary
threshold sebagai ambang batas persentase suara yang harus dicapai oleh sebuah partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen memiliki implikasi yang signifikan dalam sistem politik suatu negara, mempengaruhi representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan dinamika kompetisi politik. Konsep tersebut dapat membantu mencegah fragmentasi parlemen dengan memastikan bahwa hanya partai-partai yang memperoleh dukungan signifikan dari pemilih yang dapat memasuki parlemen. Hal ini membantu meminimalkan potensi instabilitas dan ketidakstabilan politik. Apalagi terhadap sistem yang cenderung terfragmentasi, ambang batas bertindak sebagai mekanisme untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di parlemen. Hal ini dapat membantu memfasilitasi pembentukan mayoritas yang kuat dan pemerintahan yang efisien.”

Tri Sulistianing and Luthfi Widagdo Eddyono presented their paper on Halal Certification in Indonesia at a two-day farewell symposium honoring the esteemed career of Prof. Nico Kaptein. The event, titled “Farewell Symposium – Prof. Nico Kaptein: From the Past to the Future: Islam and Religious Authority in Indonesia,” was organized in collaboration between the Faculty of Islamic Studies at the Indonesia International Islamic University (UIII) and the Office of Leiden University in Indonesia, and took place on August 29-30, 2023.
The symposium, which took place at the UIII campus in Depok, brought together prominent academics, researchers, and students interested in the intersections of Islam, society, and religious authority in Indonesia. Prof. Kaptein’s retirement marked the end of a distinguished career as Professor of Islam in Southeast Asia at the Leiden University Institute for Area Studies, officially retiring in May 2023. Throughout his career, he has made significant contributions to the scholarship of Islam and Muslim societies in Indonesia.

Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono present the paper “Electoral Change or Electoral Reform? Analysis Of Decision Number 116/PUU-XXI/2023 Related to The Parliamentary Threshold” on iEIP-2024, 4th Annual Virtual Electoral Integrity Conference on July 8-12, 2024.
Tri Sulistianing Astuti, Team Leader of the Center for Democratization Studies, presented a paper titled “Dynamic of The Indonesian Constitutional Court Decision Regarding the Legalization of Medical Marijuana” at the 2024 International Conference Drug and Research (ICRC) by Atmajaya University on May 15, 2024.




Tri Sulistianing Astuti, Team Leader of the Center for Democratization Studies, presented a paper titled “Local Government’s Coordination Capacity in Reducing Stunting Prevalence” at the 2024 Northern Illinois University’s annual Southeast Asian Studies Student Conference by Northern Illinois University on April 6, 2024.


Tri Sulistianing Astuti , Team Leader of the Center for Democratization Studies, presented a paper titled “The Politicisation of Islamophobia: Its Role in Identity Politics in Indonesia” in the 2023 CILIS Islamic Studies Postgraduate Conference held by Melbourne Law School, on 14 November, 2023.







Luthfi Widagdo Eddyono, Research Coordinator of the Center for Democratization Studies, presented a paper during Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2023 hosted by Datum Indonesia–Perkumpulan Masyarakat Teknologi dan Kemanusiaan Indonesia on Panel 5: No One Left Behind: Pendidikan HAM, SDGs, dan Pembangunan yang Berkeadilan. His paper’ title was “66 Ikon Hak Konstitusional Warga Negara dan Pendidikan HAM di Indonesia.”

Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono, Team Leader and Research Coordinator of Center for Democratization Studies, presented a paper titled “Islamophobia in Indonesia: Its Fundamental Issues and Political Identity” in the 4th International Conference on Islamophobia: Examining the Cultural and Geopolitical Dimensions ofIslamophobia in Muslim Majority Countries held by Istanbul Sabahattin Zaim University Turkiye, on 11-13 March 2023.



Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono, Team Leader and Research Coordinator of Center for Democratization Studies presented paper during the 2nd International Postgraduate Students Conference with the theme “Legal Challenges and Opportunities in the Field of Human Rights, Democracy, and Social Justice in the Post–pandemic Era“ hosted by “the Master of Law Study Program, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada. Their paper’ title was “Polemic Of Halal Certification and Its Final Battle: Who Has the Authority?”
.”

Luthfi Widagdo Eddyono, Research Coordinator of Center for Democratization Studies, presented paper during the 2nd International Postgraduate Students Conference with the theme “Legal Challenges and Opportunities in the Field of Human Rights, Democracy, and Social Justice in the Post–pandemic Era“ hosted by “the Master of Law Study Program, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada. His paper’ title was “The 2020 Regional Election Disputes and Covid-19 Pandemic.”
.”
Tri Sulistianing Astuti, Team Leader of Center for Democratization Studies, presented paper during the 2nd International Postgraduate Students Conference with the theme “Legal Challenges and Opportunities in the Field of Human Rights, Democracy, and Social Justice in the Post–pandemic Era“ hosted by “the Master of Law Study Program, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada. Her paper’ title was “Regulation Variable of Economic Freedom Index Effect on Level of Corruption.”
.”



Oleh Tri Sulistianing Astuti
Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) pertama di Indonesia diselenggarakan pada 17 April 2019 dengan desain lima kotak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), desain lima kotak berarti setiap pemilih harus memberikan lima surat suara terpisah: satu untuk Presiden, satu untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), satu untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). satu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan satu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kabupaten/Kota) secara bersamaan. Pemilu serentak 2019 berhasil diselenggarakan dengan pencapaian-pencapaian positif dan negatif.
Pencapaian Pemilu Serentak 2019 memberikan kontribusi positif terhadap persepsi kebebasan (freedom perception) Indonesia di dunia. Freedom House (2021) mengindeks Indonesia sebagai negara partly free country dengan peringkat 59 dari 100 negara. Indeks Freedom memberikan skor tinggi pada proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebagai bagian dari pelaksaanaan hak politik. Pertama, disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 secara garis besar dianggap bebas dan adil oleh pemantau pemilu internasional. Meskipun terjadi juga dilaporkan adanya penyimpangan pemungutan suara terbatas. Kedua, perwakilan legislatif nasional saat ini dianggap dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Ketiga, undang-undang pemilu dan kerangka hukum pemilu dianggap sebagian besar demokratis dan sebagian besar dipandang tidak memihak. Namun, disebutkan para aktivis mengkhawatirkan independensi otoritas, Bawaslu dan KPU karena institusi-institusi tersebut harus melakukan konsultasi yang bersifat mengikat dengan parlemen dan pemerintah sebelum mengeluarkan peraturan atau keputusan terkait penyelenggaraan pemilu .
Selain pencapaian positif, sayangnya, hal-hal negatif juga terjadi di pemilu serentak 2019 dan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. KPU menyatakan bahwa penyelenggaaraan pemilu serentak 2019 telah menyebabkan 894 penyelenggara pemilu lokal (KPPS) meninggal, dan 5.175 sakit karena kelelahan. Isu lain yang menjadi sorotan adalah daftar pemilih tetap (DPT) dan distribusi logistik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan bahwa perubahan DPT berdampak pada persiapan logistik pemilu untuk pertama kalinya . Selain itu, politisi merasa bahwa desain lima kotak menimbulkan kesulitan karena pada saat yang bersamaan politisi harus berkampanye untuk diri sendiri, partai dan kandidat presiden. Mekanisme ini juga membuat pemilih kesulitan untuk mengenali semua kandidat wakil rakyat .
Putusan Mahkamah Konstitusi
Masalah-masalah tersebut kembali berujung di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memperluas dan memberikan enam opsional model dalam pemilihan umum serentak setelah menelusuri kembali maksud semula dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa enam model pemilihan umum serentak tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 serta dianggap konstitusional berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga memberikan lima pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk memilih model pemilihan umum serentak.
Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, dan menentukan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:
Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menegaskan dirinya tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden.
Selanjutnya, dalam putusan terbaru yang membahas isu yang hampir sama, yaitu Putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Mahkamah Konstitusi menegaskan, semua pilihan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan gagasan yang muncul (original intent) selama perubahan UUD 1945. Sebagai the sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode untuk memahami konstitusi.
Hal menarik dalam Putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021 adalah respon Mahkamah Konstitusi terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pemilihan umum lima kotak menyebabkan beban kerja petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi. Menurut Mahkamah, beban kerja yang berat, tidak rasional dan tidak manusiawi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sangat berkaitan dengan manajemen pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi norma. Mahkamah menilai hal tersebut berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum yang menjadi faktor penting kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Sehingga, apa pun pilihan model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, sangat tergantung pada bagaimana manajemen pemilihan umum yang didesain oleh penyelenggara pemilihan umum, tentu dengan dukungan penuh dari pembentuk undang-undang beserta stakeholders terkait.
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, secara teknis, pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dengan struktur yang dimiliki saat ini justru lebih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis keserentakan pemilihan umum, sehingga masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan petugas penyelenggara pemilihan umum ad hoc dapat diminimalisasi dan diantisipasi.
Aspek Kesehatan dan Keselamatan
Saat ini, pandemi Covid-19 masih terus menjadi momok dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Walau demikian, penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada tetap harus dilaksanakan. Terkait dengan kondisi saat ini, dari pandangan normatif Mahkamah Konstitusi dan berkaca dari pengalaman penyelenggaraan pemilu di masa pandemi di negara-negara lain dan Pilkada serentak 2020 menunjukkan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan harus menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Kesehatan dan keselamatan adalah hak asasi manusia yang lebih utama dan dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UUD 1945. Artinya, pemilu yang demokratis tidak hanya refleksi dari proses dan hasil dari Pemilu berintegritas dan penerapan asas-asas pemilu Luber Jurdil, tetapi juga harus menjamin keselamatan penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi kebijakan di masa pandemi Covid-19 yang menciptakan kebiasaan baru diperlukan untuk diadopsi dalam administrasi dan peraturan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
Mengingat kondisi new-normal ditengarai masih akan berlanjut terus, maka penyelenggaraan Pemilu 2024 harus mengadopsi penanganan pandemi Covid-19, terutama terkait aturan kebiasaan baru dalam bingkai protokol kesehatan. Untuk itu, dari setiap tahapan Pemilu 2024, harus ada kebijakan pembatasan sosial yang mencakup aturan tentang persyaratan kondisi dan kapasitas tertentu untuk area publik dan kegiatan yang melibatkan pertemuan massal dengan jangka waktu tertentu. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 harus menjadi prioritas dan bagian penyelenggaraan Pemilu 2024. Pengaturan pembagian kewenangan penyelenggara Pemilu 2024 dan Satgas Covid-19 sebagai bagian dari penerapan new normal di masyarakat juga perlu dipikirkan dan dikaji lebih lanjut.
Tulisan ini dimuat di Majalah Konstitusi.

Sejarah hukum merupakan kajian yang selalu menarik dan mencengangkan. Ketika kita mengetahui sesuatu peristiwa yang menciptakan hukum secara kronologis maka mau tidak mau akan mempengaruhi cara kita memaknai hukum itu sendiri. Cicero pun mengatakan, “History is the witness that testifies to the passing of time; it illumines reality, vitalizes memory, provides guidance in daily life and brings us tidings of antiquity.”
Buku ini yang ditulis oleh Luthfi Widagdo Eddyono (Research Coordinator, Cedes) adalah merupakan kumpulan tulisan yang menceritakan tokoh dan juga peristiwa dalam pembentukan konstitusi, serta dinamika di awal revolusi Indonesia. Tulisan-tulisan dalam buku ini mendeskripsikan kejadian, tetapi juga tidak memisahkan ketokohan tertentu yang mungkin saja luput dari perhatian khalayak ramai, akan tetapi sungguh memberi kesan dan pemahaman dari proses pembahasan yang menghasilkan norma konstitusi
Pemanfaatan energi pada umumnya bersumber pada energi tidak dapat diperbarui (non renewable energy) dan energi dapat diperbarui (renewable energy). Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dilakukan dalam bentuk hidro, panas bumi, angin, surya, kelautan dan biomassa. Terkait dengan pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung, pada tanggal 20 September 2017, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016. Putusan ini menjadi salah satu landmark decision Mahkamah Konstitusi karena dua hal. Pertama, inilah putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama (dan yang terakhir) terkait pemanfaatan panas bumi sebagai bagian dari bidang urusan energi dan sumber daya mineral. Kedua, Mahkamah Konstitusi telah menjawab pertanyaan siapakah yang berwenang “menguasai” cabang produksi panas bumi, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
Tulisan yang disusun oleh Tri Sulistianing Astuti (Team Leader, Cedes) dan Luthfi Widagdo Eddyono (Research Coordinator, Cedes) ini menganalisis secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016 dengan maksud melihat kepastian hukum dan kemanfaatan kewenangan pemerintah pusat atas pengelolaan pemanfaatan tidak langsung panas bumi. Selain itu, tulisan ini bermaksud melihat dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasilnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016 telah memberi kepastian hukum terkait pengaturan kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, termasuk kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Pusat. Pada perkembangan selanjutnya pengaturan panas bumi diatur dalam UU Cipta Kerja yang dinyatakan secara formil inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, perbaikan UU Cipta Kerja terkait pengaturan panas bumi perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016.
Arus modal keluar dan nilai tukar rupiah pada periode awal pandemi membuktikan Covid-19 berdampak pada perekonomian. Sementara itu, Bank Indonesia diberi mandat untuk menciptakan dan memelihara stabilitas rupiah. Mempertimbangkan dampak Covid-19, pemerintah menerbitkan UU No. 2 Tahun 2020 yang memberikan Bank Indonesia peran strategis dalam pengendalian moneter dan pendanaan pemerintah saat pandemi. Tulisan ini mengkaji pengaturan hukum di bidang moneter pada masa pandemi Covid 19, serta menganalisis pembangunan hukum dan kepastian kebijakan moneter selama pemulihan ekonomi Indonesia dengan pendekatan hukum normatif dan studi pustaka. Analisa dilakukan pada kebijakan dan indikator moneter yang diterbitkan pada era pandemi.
Dari hasil penelitian yang disusun oleh Tri Sulistianing Astuti (Team Leader, Cedes) dan Luthfi Widagdo Eddyono (Research Coordinator, Cedes) ini dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia berhasil melaksanakan pembangunan hukum dan kepastian kebijakan moneter dengan mencapai sasaran inflasi 3% + 1; nilai tukar rupiah tetap stabil 14.400-14.600 terhadap dolar. Namun, terdapat potensi pelanggaran regulasi moneter terkait kewenangan baru Bank Indonesia sebagai pembeli di pasar perdana obligasi, belum ada batasan waktu pasti kebijakan moneter pandemi Covid-19 berakhir, serta potensi penyalahgunaan kewenangan melalui insider trading dan kickback walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 sebenarnya juga telah memberi putusan tentang batas waktu dan imunitas.

Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono, Team Leader and Research Coordinator of Center for Democratization Studies, presented paper during “The 2nd International Conference on Law, Human Security, and Society” organized by Faculty of Law, Atma Jaya Chatolic University Indonesia, 8 December 2022. Their paper’ title was “Constitutional Rights of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia”.


Tri Sulistianing Astuti and Luthfi Widagdo Eddyono, Team Leader and Research Coordinator of Center for Democratization Studies, presented paper during “The 2nd International Conference on Law, Human Security, and Society” organized by Faculty of Law, Atma Jaya Chatolic University Indonesia, 8 December 2022. Their paper’ title was “Data Privacy Concern on PeduliLindungi: A Walkthrough Study.”


Tri Sulistianing Astuti, Team Leader Center for Democratization Studies Jakarta, present her paper on the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021).
Abstract
The Indonesian Constitutional Court has rejected the judicial review of concurrent general elections’ constitutionality in Decision No. 55/PUU-XVII/2019 on 26 February 2020. The Constitutional Court rejected the entire judicial review of Law No.7/2017 considering General Elections and Law No. 1/2015 considering Regional Head Elections. Association for Elections and Democracy (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)) submitted this issue as the 2019 concurrent general elections with the five-box design were inconsistent with the Election Principles in the Indonesian Constitution 1945 (UUD 1945). Surprisingly, the Constitutional Court decided on six possible models in the concurrent general election besides the rejection. Even though this decision was issued before pandemic Covid-19, the options significantly impact the next concurrent general elections in the new-normal era. This paper reviews the dynamics of the decision-making process on the concurrent general elections policy in an integrative negotiation approach to understanding the Constitutional Court by juridical method and desk study. Through analyzing Decision No. 55/PUU-XVII/2019, it appeared that the Constitutional Court has succeeded in accommodating the petitioner’s necessities and referring to the implementation of elections policy effective and efficient according to the mandate of UUD 1945. In conclusion, the integrative negotiation approach applied in the decision-making process produced the six best possible options to conduct simultaneous elections in a new-normal society.
https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclhr-21/125963854

On the final session of “The 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium (also known as 2021 ICCIS), Tri Sulistianing Astuti, Team Leader of Center for Democratization Studies, Jakarta present her paper.
https://www.youtube.com/live/VP6BzJHFwr8?feature=share&t=10374
Astuti shared about the freedom of speech and religion as the fundamental rights of everyone in a democratic country. She believed that freedom of speech allowed the media to find the truth in the form of innuendo and satire as an expression. However, she admitted that innuendoes and satire as a way of expressing and finding truth did more harm than good to the religious aspect of the society. She took the example of a satire cartoon called Charlie Hebdo which became an issue of debate.
In her research, Astuti aimed to answer 2 (two) questions. First, how freedom of speech and religion got mixed and tangled in innuendoes or satire. Second, how the government created the boundary concerning religion-related satire based on the proportionality test for Indonesians as religious issues were easily misused and resulting in violence.
“As a conclusion, religious innuendos or satire as an expression should be restricted in the case of blasphemy based on the proportionality contained in Article 28J Paragraph (2) of the constitution. It (the restriction) considers the contain and purpose of the innuendoes, writer’s role, political context while respecting the ethics, races, and others. That the sensitive issue among the religious community in Indonesia and restriction of those expressions should be regulated in laws to prevent the misunderstanding of religion-related satire and causing it to be blasphemous in the Court’s decision,” she explained.
On a side note, the international symposium would be held on 15-16 September 2021 using the hybrid method (virtual and on-site) in Bandung, West Java. Previously, the Court had hosted similar programs: 2017 ICCIS in Solo, 2018 ICCIS in Yogyakarta, and 2019 ICCIS in Bali. Due to the pandemic, the program was halted in 2020. ICCIS itself was a global academic forum held annually to discuss the matters, ideas, and challenges of constitutional law, human rights, and democracy. This year it focused on religious issues in the context of constitutional rights. The Center of Case Research of the Constitutional Court opened the chance for academics to send out their articles and selected articles would publish in the Court’s journal called Constitutional Review.
Source: https://en.mkri.id/news/details/2021-09-16/Questioning+Constitutionalism+of+Religious+Freedom+and+Fighting+Extremism+and+Terrorism

Pada 9 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tahapan pertama akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Tahapan terpenting yaitu pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 dan 26 Juni 2024 untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden putaran kedua jika ada. Seluruh tahapan akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dengan pengucapan sumpah/janji pemenang Pemilu.
Keseluruhan terdapat 11 tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu: perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa kampanye Pemilu; Masa Tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Diskusi ini akan mengulas mengenai Seluk Beluk Kampanye Pemilu 2024 dan Keberadaan Pemantau Pemilu yang sangat penting untuk mengkaji proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah dimulai.
Saksikan live streaming youtube tanggal 3 November 2022 di podcast Mata Dunia dan CEDES
Tri Sulistianing Astuti, Team Leader Center for Democratization Studies Jakarta, presented her paper on Agricultural Resources and Rural Institutional Development #2 – 16th IRSA International Conference.
The 16th Indonesian Regional Science (IRSA) International Conference aims to encourage more discussion on the current policies and programs in institutional strengthening and human capital development. Agricultural Natural Resources and Rural Institutional Development Regular Session was held on Date: 12th July 2021 Time: 4:30 PM – 6:00 PM.


Buku “Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh” (KKR Aceh) memiliki kebaharuan hukum dalam tataran akademis danpraktis. Pada tataran akademis, buku ini memberikan elaborasianalitis bahwa positivisme hukum terbangun dan akan terus terbentuk sebagai sebuah proses interpretasi dan konstruksi hukum dalam mencari dan mendefinisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kedua proses tersebut menjawab tantangan terbesar dalam positivisme hukum bahwa sistem hukum harus menyediakan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang timbul.
Buku ini menyajikan fakta kejadian dan fakta hukum secara berimbang dan runtut dalam konstruksi siapa, apa, bagaimana,kapan, dan di mana hak dan kewajiban hukum yang timbul. Para penulis menyajikan kedua fakta tersebut sebagai dasar analisis yang mencerahkan dan menantang dalam penalaran hukum kritis,analitis dan konstruktif mengenai eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan memberikan justifikasi atau rasionalitas KKR di level nasional kelak di kemudian hari.


Museum merupakan salah satu simbol tingkat kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Selain berfungsi sebagai ruang pengetahuan, museum juga menjadi ruang pembuktian peradaban bangsa sejak masa purba hingga milenium yang menuturkan peradaban dari berbagai aspek sehingga memperkaya batin dan mencerahkan pikir.
Mari ikuti Talkshow kolaborasi Jogja Museum Lovers, Center for Democratization (CEDES) Jakarta dan Indonesia Turkey Research Community dengan tema: Museum sebagai Ruang Peradaban dan Ruang Pengetahuan
Opening speech:
Luthfi Widagdo Eddyono, S.H, M.H
Research Coordinator Center for Democratization Studies (CEDES) Jakarta dan Peneliti di Mahkamah Konstitusi
Didid Haryadi, S.Sos, M.A.
Dosen Sosiologi, Universitas Nasional Jakarta
Peneliti Center for Democratization Studies (CEDES) Jakarta, Co-founder Indonesia Turkey Research Community
Kuncoro Sejati, ST, MBA.
Founder Jogja Museum Lovers
Moderator:
Joana Zettira
Duta Museum DIY
Sabtu, 6 Maret 2021
Jam 15.00
Live streaming youtube:
Center for Democratization Studies
Semakin peduli, semakin kuat komitmennya didalam menangani, memelihara, mengembangkan, dan memperhatikan museum, maka semakin tinggilah tingkat peradaban sebuah bangsa itu.
Kini museum-museum Indonesia semakin maju sebagai perlambang bahwa bangsa Indonesia juga mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan.
Research Coordinator Center for Democratization Studies Jakarta, Luthfi Widagdo Eddyono, baru saja meluncurkan buku Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia. Mengapa dia menulis buku ini?
Membicarakan konstitusionalisme tentu harus mengaitkannya dengan hukum konstitusi yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks perkembangannya, konstitusionalisme tidak berada di ruang hampa. Terdapat dinamika yang bernilai akademis untuk diamati karena pandangan para ahli tentu tidak sama dan serupa. Buku ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai isu penting konstitusionalisme dalam kerangka hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia. Perspektif sejarah dan praktik perkembangan masa kini juga diamati dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang kerap berulang baik karena disengaja maupun karena terjadi apa adanya. Buku ini memuat berbagai pandangan ahli hukum konstitusi yang memiliki otoritas akademik. Selain itu, untuk melihat secara konstekstual pandangan ahli buku ini mengaitkannya dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan dinamika konstitusionalisme benar-benar terjadi tidak hanya pada tataran akademis tetapi juga karena ditemukan persoalan di masyarakat.
Penulis: Luthfi Widagdo Eddyono
ISBN: 978-623-231-502-0
Ukuran: 15 x 23 cm
Halaman: 194 halaman
Tahun: 2020
DINAMIKA KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA – Luthfi Widagdo Eddyono
Setiap 26 Juni diperingati sebagai “International Day in Support of Torture Victims”. Penulisan buku ini oleh Research Coordinator Center for Democratization Studies Jakarta, Luthfi Widagdo Eddyono, dimaksudkan untuk mengingatkan kembali ada sebuah konvensi internasional yang sangat penting yang telah diterima secara global oleh hampir seluruh negara di dunia dan penerapannya perlu segera dilaksanakan pada level nasional di setiap negara. Konvensi Anti Penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia.
Buku ini juga memuat politik penerapan hukum internasional yang jelas terlihat dari adanya deklarasi dan reservasi dalam ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan oleh Indonesia serta dinamika hukum hak asasi manusia. Relasi hukum tata negara dan hukum internasional juga turut dibahas mengingat Mahkamah Konstitusi telah mencoba menjawab hal tersebut, yaitu melalui dua putusannya. Pertama, Putusan Nomor 33/PUU-IX/2011 menyangkut Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (UU 38/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang merupakan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke depannya keberadaan Mahkamah Konstitusi pasca reformasi konstitusi 1999-2002 berpotensi menegakkan konvensi ini dengan menggunakannya sebagai referensi hukum internasional, demikian juga dengan konvensi internasional lainnya dapat menjadi bahan hukum bagi Mahkamah Konstitusi karena pada prinsip konvensi internasional merupakan trend hukum global.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bagian yang tidak
terpisahkan dalam manajemen perlindungan tenaga kerja.
Memastikan terselenggaranya pekerjaan dengan didukung oleh
tenaga kerja yang sehat dan produktif yang pada gilirannya mampu
meningkatkan daya saing produk/jasa yang dihasilkan merupakan
tujuan utama K3.
Kenapa K3 menjadi penting dewasa ini? Nor Wijayanti mencoba
mengulas kegagalan penyelenggaraan K3 dengan meneliti pengaruh
pengetahuan, sikap pekerjaan dan alat pelindung diri (APD) terhadap
K3.
Penulis mencoba melakukan pendekatan yang berbeda dengan
mengungkap korelasi pengetahuan, sikap dan kesediaan APD
terhadap perilaku pekerja dalam hal ini melalui studi kasus di
STIKES Surya Global Yogyakarta. Setelah melakukan review atas
pelbagai metodologi yang berkembang saat ini, penulis
menunjukkan bagaimana pengetahuan, sikap dan ketersediaan APB
dapat memberikan hasil yang berbeda pada setiap praktik K3.
Studi kasus yang disajikan dengan analisa kritis akan membantu
para pembaca memahami K3 dan faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan di organisasi. Hasil penelitian ini juga akan memberikan
manfaat bagi pembaca atau praktisi K3 lainnya untuk menentukan
strategi terbaik dalam penerapan K3. Di dalam lingkungan kerja
yang terus berubah dengan berbagai dinamikanya, optimalisasi K3
menjadi sebuah jawaban dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja
yang humanis lagi produktif.

Akhir tahun 2017 lalu, tepatnya pada 21 Desember 2017, di-launching sebuah media baru untuk anak muda. Media tersebut berisi konten-konten menarik untuk anak muda.
Peluncuran Tambo Media, nama media baru tersebut, dilaksanakan di Museum Sandi, Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga disertai sebuah Seminar “Jurnalisme Damai dan Konten Positif untuk Anak Muda” dengan bekerja sama dengan Center for Democratization Studies. Pembicara kunci, Aryo Subarkah Eddyono, menjelaskan dua hal tersebut, yaitu mengenai jurnalisme damai dan konten positif. Pembicara yang lain, Agus Mulyono yang merupakan Person in Charge Cedes, dan Bernando B. Sujibto juga menyampaikan kondisi yang terjadi di Indonesia yang menguatkan pendapat bahwa pemahaman atas jurnalisme damai sangatlah penting.
Pada pokoknya, jurnalisme damai merupakan kebutuhan konsep jurnalisme yang ingin berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Caranya adalah dengan menyediakan konten positif yang faktual dan aktual agar tetap menarik untuk dibaca. Selain itu, penting juga dilakukan penguatan pemahaman etis bagi para jurnalis agar berita yang ditulis atau diciptakan akan lebih akurat. Untuk itu, disinilah pentingnya keberadaan Tambo Media yang memposisikan medianya berbeda dari media online kebanyakan yang cenderung memberitakan sesuatu secara bombastis.
Tambo merupakan sebuah platform media terintegrasi dimana di dalamnya memuat berbagai konten yang bercerita tentang lifestyle, travel, kuliner, infodata, komunitas, kreatif, fashion dan hiburan. “Melalui artikel yang bernuansa kekinian diharapkan generasi milenial dapat menggali informasi yang bermanfaat dan dikemas dengan bahasa yang ringan,” ujar Kuncoro Sejati, pemilik Tambo Media, ketika menyampaikan sambutannya dalam peluncuran media alternatif ini.



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pemilukada merupakan masa lalu. Masa kini
adalah “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”. Hal demikian disebabkan adanya perubahan paradigma mengenai rezim dimanakah “pemilihan kepala daerah” tersebut berada.
Dahulu diyakini bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum. Hingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Pemaknaan demikian sungguh dipahami pembentuk undangundang. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan menelurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Walau demikian, Mahkamah Konstitusi untuk sementara diminta tetap menangani perselisihan tersebut.
Mahkamah Konstitusi sendiri dengan putusan-putusannya, lebih utama dalam Putusan Nomor 5/PHP.BUP-XV/2017, telah menegaskan sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus terbentuk.
Buku ini akan sangat membantu pembaca untuk memahami perubahan paradigma tersebut. Tidak hanya diperuntukkan bagi kajian historis, beberapa uraian dalam buku ini akan sangat membantu para pihak yang berminat mengikuti sidang-sidang Mahkamah Konstitusi secara langsung sebagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu Center for Democratization Studies sangat mendukung penerbitan buku ini.

Nor Hidayah, Law Researcher, accepted for the Taiwan Foundation for Democracy’s 2017 Asia Young Leaders for Democracy (AYLD) Program. After a rigorous selection process involving applicants from Asian countries, Nor Hidayah joined other distinguished young leaders in Taipei for the program between July 31 and August 8, 2017.
As a member of the Taiwan Foundation for Democracy’s (TFD) 4th Asia Young Leaders for Democracy (AYLD), Nor Hidayah, adopted a joint declaration vowing to promote democracy and combat the democratic recession, as all participants marked the conclusion of the nine-day workshop in Taipei.
The declaration issued by the 2017 AYLD’s 20 members, which come from 13 Asian countries and elsewhere, seeks to ensure democracy and fundamental rights in Asia through seven areas. They include combating alternative models of democracy; fighting against disinformation; rejecting extremism; refusing discrimination against migrants, minority groups and the LGBTQIA community; supporting political participation of unrepresented groups; ensuring free and fair elections; and combating uneven development.

Luthfi Widagdo Eddyono, on behalf of Cedes, has participated in the Istanbul Seminars 2016 with a grant from the Reset-Dialogues on Civilizations. The 9th edition of the Istanbul Seminars held on May 24-28, 2016 with the topic: “Religion, Rights and the Public Sphere.” The conference takes place at Istanbul Bilgi University and attracts a considerable audience of scholars and students from all over the world. The Istanbul Seminars 2016 have discussed how much religious pluralism is a matter of politics, law and the economy and to what extent it also concerns theology.

Person in Charge, Agus Mulyono, accepted for the Taiwan Foundation for Democracy’s 2016 Asia Young Leaders for Democracy (AYLD) Program. After a rigorous selection process involving applicants from 23 countries, Agus will join other distinguished young leaders in Taipei for the program between August 7 and August 20, 2016. The program features lectures by eminent scholars and practitioners in the fields of human rights and democracy.
Harianjogja.com, SLEMAN — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara 103/PUU-X tahun 2012 mengenai tata kelola perguruan tinggi dapat membuka “celah” terjadinya korupsi.
Peneliti Center For Democratiozation Studies, Luthfi Widagdo Eddyono mengungkapkan putusan tersebut memungkinkan beberapa persoalan terjadi. Pertama bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), kedua penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri, ketiga penjaringan mahasiswa baru berprestasi yang berstatus 3T, keempat pendanaan dari dunia industri maupun masyarakat dan kelima pengelolaan hak kekayaan perguruan tinggi dalam UU no.12 tahun 2012.
Pada akhirnya, MK telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.
“Faktanya pemerintah memberi fleksibilitas dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN atau dari sumber dana lainnya, yang tentu saja rentan disalahgunakan” kata Luthfi Widagdo Eddyono saat menjadi pembicara dalam Anti-Corruption Summit II seminar Presentasi Call For Papers dengan Tema “ Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi” di Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Senin (24/10/2016) seperti dikutip dari rilis yang Harianjogja.com terima.
Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hary Budiarto menambahkan kampus diharapkan mampu mengambil peran sebagai pemutus mata rantai perilaku dan kejahatan koruptif. Sebab perguruan tinggi melahirkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dengan beberapa karakteristik seperti tidak korup, cerdas secara individual dan institusional, komitmen penuh pada kepentingan umum dan setia pada visi dan misinya.
“Pemberantasan korupsi butuh keteladanan. Keteladanan dari pemimpin, guru, dan dosen yaitu kejujuran, sikap hidup sederhana. Dari keteladanan tersebut akan menjadi viral yang menular kepada orang lain sehingga menjadi gerakan yang bersifat kolektif” tutur Hary.
Acara yang digelar atas kerja sama antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, KPK dan Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) ini turut dihadiri pembicara seperti Agus Riswanto Achmad, (Dosen UNS) Nadia Sarah (Advisor Sustainability For indonesia), Dwi Siska Susanti, (Mitra Juang Indo) dan Erwin natosmal Oemar (Indonesian legal Roundtable).
Sumber: http://www.harianjogja.com/baca/2016/10/25/pendidikan-antikorupsi-putusan-mk-ini-dapat-menjadi-celah-seperti-apa-763229
YOGYA (KRjogja.com) – Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi
Pemberantasan korupsi dapat diatasi melalui pendekatan upaya penindakan, pencegahan secara sistematis hingga pendidikan publik dengan menyertakan partisipasi publik secara luas.
Karena itu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PUKAT UGM menyelenggarakan Anti Corruption Summit II seminar Presentasi Call For Papers dengan Tema ‘Tata Kelola Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Korupsi’ di Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Senin (24/10/20156). Dalam acara tersebut dihadiri pembicara seperti Dr. Agus Riswanto Achmad, S.H., M.H (Dosen UNS) Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H (Peneliti Center For Democratiozation Studies), Nadia Sarah, S.Si (Advisor Sustainability For indonesia), Dwi Siska Susanti, S.H.,M.H (Mitra Juang Indo) dan Erwin natosmal Oemar (Indonesian legal Roundtable) dengan keynote speaker Dr. Hary Budiarto, M.Kom (Deputi Informasi dan Data KPK).
Deputi informasi dan Data KPK Dr. Hary Budiarto, M.Kom. menuturkan kampus diharapkan mampu mengambil peran sebagai pemutus mata rantai perilaku dan kejahatan koruptif. Dalam hal ini perguruan tinggi untuk dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berintegritas dengan beberapa karakteristik seperti tidak korup, cerdas secara individual dan institusional, komitmen penuh pada kepentingan umum dan setia pada visi dan misinya.
“Pemberantasan korupsi butuh keteladanan. Keteladanan dari pemimpin, guru, dan dosen yaitu kejujuran, sikap hidup sederhana. Dari keteladanan tersebut akan menjadi viral yang menular kepada orang lain sehingga menjadi gerakan yang bersifat kolektif” tutur Hary.
Nadia Sarah, S.Si mengungkapkan praktek korupsi di perguruan tinggi karena tidak adanya aspek akuntabilitas dan transparasi. Titik rawan terjadinya korupsi yakni dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta benturan kepentingan.”Mestinya pejabat kampus paham betul UU No.12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bagaimana hak dan kewajibannya” kata Nadia Sarah. (*)
Sumber: http://krjogja.com/web/news/read/13580/Perguruan_Tinggi_Diharapkan_Putus_Mata_Rantai_Korupsi

Kuncoro Sejati, Team Leader for Technology and Operational Management, joined a management program from Fujitsu-JAIMS Foundation called 2016 Global Leaders for Innovation and Knowledge, which features a multi-campus network of four countries: Japan, the U.S.(Hawaii), Singapore, and Thailand.
The program cultivates innovative leaders with practical wisdom through learning management theories, liberal arts, and methodology & practice.

Research Coordinator, Luthfi Widagdo Eddyono, accepted for the Taiwan Foundation for Democracy’s 2015 Asia Young Leaders for Democracy (AYLD) Program. After a rigorous selection process involving applicants from 25 countries, Luthfi joined other distinguished young leaders in Taipei for the program between August 9 and August 22, 2015. The program features lectures by eminent scholars and practitioners in the fields of human rights and democracy.
The Taiwan Foundation for Democracy (TFD) was established with an inter-related, two-tracked mission in mind. Domestically, the TFD strives to play a positive role in consolidating Taiwan’s democracy and fortifying its commitment to human rights; internationally, the Foundation hopes to become a strong link in the world? democratic network, joining forces with related organizations around the world. Through the years, Taiwan has received valuable long-term assistance and stalwart support from the international community, and it is now time to repay that community for all of its efforts.

Fauziah Eddyono, Team Leader for Economic and Development, will participate in the Istanbul Seminars 2015 with grant from the Reset-Dialogues on Civilizations. The 8th edition of the Istanbul Seminars will be held on May 26-30, 2014 at Istanbul Bilgi University. Topic: “Politics Beyond Borders. The Republican Ideal Challenged by the Internationalization of Economy, Law and Communication.” The conference takes place at Istanbul Bilgi University and attracts a considerable audience of scholars and students from all over the world.
Oleh Tri Sulistianing Astuti

Judul buku : Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Penulis : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.
Penerbit : Konpress (Konstitusi Press)
Tahun : 2014
Halaman : xxxii + 332
“Make them for the public good”.
John Locke (Two Treaties of Civil Goverment)
Sepotong pendapat John Locke tersebut mengisyaratkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif adalah yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat. Kutipan ini cukup mengganggu jika disodorkan pada realitas hukum Indonesia di era reformasi. Salah satu fenomena penting di era reformasi adalah maraknya judicial review di Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan meningkatnya kuantitas produksi undang-undang yang disahkan oleh DPR. Kuantitas dan kualitas produk tidaklah selalu linier, justru cenderung dipertanyakan melalui pisau judicial review. Dr. Bayu Dwi Anggono mewacanakan dan menulisnya dalam buku Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.
Buku ini bersumber dari disertasi Dr. Bayu Dwi Anggono pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Asas Materi Muatan yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)”. Alurnya runtut memberikan logika pentingnya asas materi muatan undang-undang yang tepat pada peningkatan kualitas undang-undang di Indonesia.
Buku dibagi menjadi lima bab. Diawali dengan penjabaran penelitian dan teori konseptual tentang undang-undang, meliputi pemahaman, pembentukan, dan pengujian undang-undang. Studi di empat negara (Belanda, Jerman, Finlandia, dan Vietnam) memberikan deskripsi dan komparasi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas undang-undang di Indonesia.
Menarik untuk disimak, sejak bab pendahuluan penulis telah menyajikan kontradiksi atas teori hukum yang baik, yakni hukum yang harus didasarkan pada prinsip manfaat, diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas, justru tidak terlihat pasca Orde Baru. Hal ini terkalkulasi dengan membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan hingga menimbulkan hyperregulation. Prof. Dr. Maria Farida Indrati S, S.H., M.H., dalam pengantarnya, sepakat dengan penulis bahwa sejak bergulirnya reformasi yang ditandai perubahan UUD 1945, telah terjadi perubahan pemahaman dan paradigma dalam pembentukan undang-undang. Ada kecenderungan pembentuk undang-undang semakin boros dan terlalu membesar-besarkan persoalan (hal xiii). Hiper regulasi ini yang menjadi titik tolak atas pentingnya pemahaman dan penggunaan asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan undang-undang yang berkualitas tinggi. Asas materi yang tepat merupakan aspek yang sangat penting dan dominan dalam pembahasan dalam bab selanjutnya.
Penulis buku, yang berprofesi sebagai Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, menuturkan urgensi keberadaan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Uraian tersebut akhirnya akan mengerucut pada asas materi muatan yang tepat, sebagai salah satu asas penting dalam pembentukan undang-undang. Sentilan terhadap kemungkinan undang-undang kadang-kadang membahayakan kebebasan warga negara juga tersirat dalam bab dua. Produk hukum yang lahir dari proses legislasi tidak dapat lepas dari pengaruh politik sehingga kontrol diperlukan dalam pembentukannya (hal. 45).
Untuk mendukung premisnya, penulis pun menyertakan pendapat ahli hukum di Indonesia perihal pentingnya asas materi muatan undang-undang Indonesia. Disertai legitimasi dalam aturan-aturan hukum Indonesia, mulai dari payung hukum Indonesia (tegas dalam UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang) hingga ditegaskan melalui serangkaian argumentasi aturan-aturan yang perlu untuk melindungi hak dasar, warganegara, pembagian kekuasaan, dan pengaturan pendapatan belanja penyelenggara negara (hal. 63-99).
Menguji Undang-Undang
Ketidaktepatan materi muatan dan hiper regulasi ini membuka wacana akan hak menguji undang-undang sebagai penjaga kualitas produk hukum. Kilas balik sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dialektika hak menguji undang-undang dimulai sejak sidang BPUPKI pada 15 Juli 2015, atas usulan M. Yamin tentang perlunya Mahkamah Agung memiliki hak “membanding-bandingkan undang-undang”. Namun, sidang ini tidak memberikan keputusan sehingga UUD 1945 sebelum perubahan tidak mencantumkan aturan perubahan. Mahkamah Agung sempat mendapatkan hak menguji, tetapi sebatas pengujian pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hal. 150).
Ide pengujian undang-undang berlanjut di era reformasi dan memberikan hak menguji kepada MPR berupa pengujian UUD 1954 dan Ketetapan MPR. UUD 1945 setelah Perubahan akhirnya menuntaskan dialektika ini melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji UUD yang dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (hal. 151).
Menurut Dr. Bayu, MK dalam kurun waktu 2005-2009, telah menghasilkan 150 Putusan atas 73 UU yang diajukan judicial review. Dari jumlah putusan tersebut, 40 diantaranya dikabulkan (hal. 234). Tingginya angka judicial review menunjukkan bahwa kualitas produk legislasi DPR masih buruk. Selain itu, pasca reformasi (1999-2012), telah hadir 200 undang-undang non undang-undang kategori daftar kumulatif terbuka, 14 undang-undang diantaranya diindikasikan tidak memuat materi yang seharusnya diatur (hal. 293). Pada titik inilah hiper regulasi menjadi berbahaya karena merugikan secara substansi, anggaran, dan bahkan bagi kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang diidamkan justru menjadi eksekutor yang salah karena penerapan asas materi yang tepat diabaikan sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas.
Meningkatkan kualitas undang-undang di Indonesia menjadi pokok bahasan yang menarik untuk dicermati karena muncul solusi atas masalah hiper regulasi. Dimulai dari memahami proses pembentukan undang-undang. Secara garis besar, penulis membagi periode pembentukan undang-undang menjadi dua, yakni periode pembentukan undang-undang sebelum perubahan UUD 1945, dan periode pembentukan undang-undang pada UUD 1945 setelah perubahan. Titik berat pembahasan adalah pada badan legislator dan proses legislasi yang terjadi.
Realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menjadi tolok ukur kinerja DPR sebagai badan legislator, tidak terpenuhi disebabkan fraksi-fraksi cenderung mengabaikan kinerja legislasi dan ketidakjelasan politik legislasi. Banyak fraksi yang tidak memiliki kebijakan RUU mana saja yang layak untuk diperjuangkan menjadi prioritas. Ditambah lagi, mayoritas komisi di DPR lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran (hal. 237). Muaranya adalah kegagalan politik legislasi, yakni pemerintah dan DPR gagal merumuskan kebijakan pengaturan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
Kegagalan ini akhirnya mendorong berbagai kelompok/lembaga berlomba-lomba mengajukan topik atau judul undang-undang sehingga wajar ditemukan banyak undang-undang yang disahkan tidak masuk dalam Prolegnas. Kriteria RUU yang layak jadi prioritas dan diajukan dalam Prolegnas terlalu umum sehingga jumlah RUU dalam Prolegnas terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Jumlah yang banyak serta kualitas RUU yang diajukan belum mempertimbangkan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi sehingga kinerja legislasi rendah dan terkesan seadanya karena tanpa persiapan bahan yang memadai. Akibatnya, pembahasan RUU dengan waktu yang relatif pendek tidak dapat menghasilkan kualitas yang relatif baik (hal. 240).
Rendahnya partisipasi masyarakat, belum terlembagakannya fungsi legislative review/excecutive review, efektivitas kinerja dan kualitas Badan Legislasi, waktu pembahasan RUU yang dihabiskan untuk hal teknis kalimat, kinerja legislasi pemerintah yang menunjukkan kurangnya tanggungjawab dalam pembuatan undang-undang, anggaran yang tidak tepat sasaran, hingga pengaruh asing dalam pembentukan undang-undang yang menyentil syarat International Monetary Fund di masa krisis, dianggap penulis buku sebagai masalah dalam penyusunan dan realisasi Prolegnas. Permasalahan tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk mencermati implementasi reformasi regulasi empat negara, yakni Belanda, Jerman, Finlandia, dan Vietnam.
Reformasi Regulasi Empat Negara
Reformasi regulasi dipaparkan sebagai motor yang lebih kompleks dibandingkan deregulasi. Deregulasi hanyalah salah satu bagian dari reformasi regulasi. Mengambil intepretasi dari Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), reformasi regulasi merujuk pada perubahan untuk meningkatkan kualitas regulasi, yaitu meningkatkan kinerja, efektifitas biaya, kualitas hukum peraturan, serta terkait formalitas pemerintah (hal. 259).
Dari empat negara yang dikaji, dapat ditarik benang merah bahwa reformasi regulasi adalah hal yang lazim dilakukan untuk mengatasi rendahnya mutu regulasi serta mengakomodir kebutuhan masyarakat dan negara yang bersifat dinamis. Hiper regulasi, beban biaya yang membengkak, dan berkurangnya penghormatan terhadap hukum menjadi pemantik reformasi regulasi.
Belanda menerapkan enam kriteria untuk regulasi yang berkualitas di Kementrian Kehakimnan, yang mencegah tumpang tindih regulasi serta fokus pada manfaat dan efesiensi (hal. 260-262). Jerman membuat kebijakan Programme Bureaycracy Reduction and Better Regulation, legal quality inisiatives, legislative simplification initiative, dan pembentukan data base (hal. 263). Finlandia meningkatkan kualitas undang-undang dengan menetapkan agenda perbaikan legislatif, membentuk komite regulasi dan konsultatif, menerapkan kehati-hatian mulai dari proses perancangan, evaluasi terhadap altenatif dan dampak serta implementasi sistem mutu dan data base (hal.264-266). Vietnam menjawab tuntutan warganegara dan dunia usaha akan kebutuhan regulasi yang berkualitas dengan Project 30 dan Law on the Promulgation of Legal Normative Documents.
Salah satu terobosan Vietnam yang menarik untuk dilihat implementasinya di Indonesia adalah dukungan resmi terhadap penilaian dampak regulasi (regulatory impact asessment) sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas regulasi baru (hal. 268). Namun, sayangnya penulis buku tidak memberikan eloborasi yang lebih mendalam atas inovasi ini.
Dukungan resmi menjadi alat yang penting untuk menindaklanjuti analisa/masukan atas dampak regulasi dari berbagai pihak. Saat ini, pemerintah Indonesia masih merespon secara sporadis. Mayoritas inisiatif judicial review diajukan oleh individu/lembaga non pemerintah. Padahal, pemerintah pun berhak atau malah berkewajiban untuk mengajukan judicial review atas regulasi yang tidak tepat sasaran/berkualitas rendah.
Urgensi Asas Materi Muatan
Pada bagian terakhir, penulis menyimpulkan alasan yang mendasari urgensi asas materi muatan yang tepat, yakni: (i) merupakan sarana untuk memastikan dalam pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat yaitu materi yang memang seharusnya diatur dengan undang-undang; (ii) berguna untuk memudahkan pembentuk dalam mengindentifikasi kebutuhan pembentukan undang-undang; dan (iii) sebagai sarana sarana pembeda untuk mengetahui materi apa yang harus diatur dengan undang-undang dan materi apa yang harus didelegasikan pengaturannya kepada peraturan di bawah undang-undang (hal. 291-292). Asas materi muatan yang tepat berpotensi besar untuk membendung hiper regulasi pasca reformasi, tentunya tanpa mengabaikan proses pembuataan undang-undang, proses pengujian, dan peran pemerintah harus berjalan simultan untuk meningkatkan kualitas undang-undang.
Hal yang kontroversial menurut Dr. Bayu adalah temuannya dalam kesimpulan mengenai 14 undang-undang dari 428 undang-undang (atau berjumlah 200 apabila dikurangi undang-undang kategori daftar kumulatif terbuka) yang dibentuk sejak 1999-2012 terindikasi tidak memenuhi butir-butir materi muatan undang-undang atau dengan kata lain “bukan materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang”.
Dengan menanggalkan atribut komersial, penerbitan tulisan disertasi menjadi buku tentunya bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih umum bahkan awam terhadap subyek perundang-undangan. Dari segi tata bahasa, alur penulisan, dan pilihan kata, buku ini mudah untuk dibaca dan runtut sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap pemasalahan. Namun, perlu kiranya penulis mempertimbangkan untuk memberikan porsi lebih banyak tentang pembahasan metode reformasi regulasi di empat negara atau malah lebih untuk memberikan kelegaan yang lebih lama. Ditambah lagi, kajian ini menarik dan memiliki nilai jual tersendiri untuk menjangkau audiens beragam serta layak dieksplorasi untuk penerbitan edisi berikutnya.
Terlepas dari kekurangan buku ini, yang sangat minim tentunya dibandingkan kelebihannya secara akademis maupun praktis, buku ini wajib untuk dimiliki oleh mahasiswa/aktivis/pembaca yang berminat dan bergelut pada subjek perundang-undang sebagai referensi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschatf). Kajiannya yang lugas menjadi pengingat bahwa hiper regulasi dapat dicegah sejak awal pembentukan undang-undang, yakni dengan kepedulian atas asas materi muatan tepat.
#Telah dimuat di Majalah Konstitusi, Februari 2015

Oleh Fauziah Eddyono
Peneliti Center for Democratization Studies
Judul Buku : Membelenggu Ekspresi:Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia
Penulis : Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin
Penerbit : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Terbitan : Cetakan I, 2014
Jumlah halaman: 72
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 5/PUU-VIII/2010 pada pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyatakan bahwa bilapun terdapat pembatasan hak asasi manusia haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pengaturan wajib dalam Undang-Undang sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan dan pengaturan tersebut melibatkan publik yang diwakili DPR. Akan tetapi berdasarkan temuan Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)sebagaimana disebutkan dalam buku ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang memiliki kecenderungan bermasalah karena wadah pengaturannya tidak tepat. (halaman 10). Selain itu, masih banyak lagi temuan khususnya terkait dengan pemblokiran/penyaringan konten internet dan munculnya kriminalisasi bagi pengguna internet di Indonesia yang patut untuk dikaji.
Pemblokiran/penyaringan konten internet adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikarenakan kepada akses informasi di internet. Umumnya menggunakan teknik alamat dan teknik konten. Walau demikian mekanisme yang digunakan dalam penyaringan dan pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang tersedia untuk tindakan tersebut. Pilihan mekanisme juga sangat tergantung pada kemampuan dari institusi yang meminta dilakukannya penyaringan/pemblokiran, khususnya sejauh mana mereka memiliki akses kepda pihak-pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka. Bahkan terdapat tren terbaru pemblokiran berdasarkan waktu (just in time) yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. (halaman 11-15).
Dalam konteks Indonesia, Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, menyebutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dari yang semula hanya menjadi regulator kemudian berkembang menjadi pengawas informasi sekaligus. Khususnya sejak diundangkannya UU ITE, kementerian tersebut mulai melakukan penindakan terhadap sejumlah konten internet yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti penodaan agama, terorisme, dan pornografi.
Membelenggu Ekspresi dengan Ancaman Pidana
Salah satu poin penting dalam buku ini adalah mengenai jeratan hukum dan pengenaan sanksi pidana bagi penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika atau melalui internet. Banyak kasus yang timbul menunjukkan bahwa (i) semua medium yang menggunakan sarana elektronika menjadi subjek yang dapat dikenai sanksi; (ii) kritik dan pendapat sering berujung pada pelaporan ke polisi sebagai pencemaran nama baik; (iii) penggunaan sarana hukum pidana seringkali menjadi pilihan utama; dan (iv) menyasar hak asasi manusiapir semua kalangan. (halaman 26). Padahal, menurut Frank La Rue—seorang Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berpendapat, dan Berekspresi— pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dalam era intenet, setiap individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat intenet tidak perlu dijatuhkan.
Di sinilah pentingnya buku yang ditulis Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin ini, karena menunjukkan analisis terhadap dampak dari kebijakan konten internet di Indonesia dalam kaitannya dengan internet sebagai alat yang diperlukan untuk mewujudkan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia.
Buku ini mengkaji dengan detail mengenai Undang-Undang maupun rancangan peraturan perundang-undangan mengenai konten internet yang materinya masih sangat terbatas dan belum secara khusus membahas aturan mengenai konten internet, termasuk pengawasan dan pengendaliannya. Selain itu, buku ini juga menguraikan mekanisme dan dimensi pemblokiran dan penyaringan konten internet disertai analisis terhadap pemblokiran dan penyaringan konten internet di Indonesia, pemblokiran dan penyaringan dengan alasan penodaan agama, dan pemblokiran dan penyaringan dengan alasan muatan pornografi.
Pada akhirnya buku ini menguraikan hasil kajian dan melakukan analisis terhadap inti permasalahan, yaitu praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan pembelengguan ekspresi dengan ancaman pidana yang mencakup perumusan UU ITE yang bermasalah dimana pada saat pembentukannya, UU ITE memang telah menuai banyak kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi eletronik yang bermuatan kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan materi yang mengandung materi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun sanksi lainnya, sehingga mengakibatkan chilling effect atau efek ketakutan yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Buku ini jugamenguraikan unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, keberadaan UU ITE sebagai bentuk kontrol terhadap publik, bagaimana penyelesaian perdata/mediasi, dan yang terutama dampak buruk UU ITE yang dilengkapi dengan berbagai kasus yang menunjukkan situasi jaminan kebebasan berpendapat dan berekespresi yang terbelenggu, baik dalam konteks pemblokiran/penyaringan akses maupun meningkatnya ancaman pemidanaan terhadap pengguna. Dimana uraian dikemas secara apik berdasarkan alur berpikir Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin yang memang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di tanah air.
Pada akhirnya para penulis tersebut merekomendasikan, di antaranya, adalah pentingnya melakukan penelaah ulang dari revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadappemberian ruang yang memadai pada pengaturan konten dan pengawasannya, serta memastikan adanya harmonisasi berbagai instumentasi internasional hak asasi manusia yang telah diadopsi di tanah air, sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Buku ini sangat baik dijadikan bahan bagi akademisi, pengacara/advokat, praktisi hak asasi manusia dan para penegak hukum, yang ingin mendudukkan permasalahan hukum terhadap konten internet tanpa mengesampingkan unsur-unsur hak asasi manusia.
#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014.
Oleh Arvie Dwi Purnomo
Peneliti Center for Democratization Studies

Judul Buku : Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Penulis : Junaiyah H. Matanggui
Penerbit : Penerbit PT Grasindo, Jakarta
Cetakan : Pertama, 2013
Tebal : vi + 161 Halaman
Bahasa Indonesia untuk bidang hukum rasanya masih asing di telinga pembacanya. Terlebih model bahasa yang digunakan berbeda dari segi istilah maupun gaya penulisannya. Acapkali kita mendengar ataupun membaca tulisan berbahasa Indonesia di bidang hukum tersebut, sering kali pula kita tak paham maksud dari bahasa tersebut. Padahal apabila dipelajari, bahasa hukum sebagaimana bahasa bidang lainnya akan mudah untuk dipahami. Kata-kata seperti menimbang, mengingat dan memutuskan merupakan contoh kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Apabila sekilas kita membacanya tentu tidaklah berbeda dengan bahasa Indonesia lainya perbedaan lebih pada kaidah dan penggunaan bahasa tersebut dalam konteks yang berbeda.
Sejatinya bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan bukan merupakan bahasa baru dalam rumpun bahasa Indonesia. Bahasa hukum memiliki kaidah maupun tata tulis yang sama dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Perbedaan yang ada lebih pada penggunaan istilah, kosakata yang penyampaian yang disesuaikan dengan kelaziman bidang tersebut. Laras bahasa hukum menggunakan gaya istilah, gaya penyampaian atau komposisi yang khas, logis, monosemantis, jelas, lugas, tepat dan benar agar terjadi kepastian hukum (hal 2). Lebih lanjut disebutkan bahasa Indonesia bidang hukum harus memenuhi syarat diantaranya bentuk kata harus benar, makna kata harus tepat,disamping memiliki istilah khas dan bernorma hukum.
Sebagaimana penggunaan bahasa Indonesia pada umumnya, bahasa Indonesia hukum juga mengenal makna, bentuk dan pilihan kata. Sehingga penulis pun berupaya memberikan pemahaman dan pembelajaran bahasa hukum sebagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia, dimulai dari makna dan hubungan makna kata seperti, sinonim, hiperonim hingga makna gramatikal dan leksikalnya hingga penyusunan kalimat dan paragrafnya. Penulis mencoba mengiring alur pemikiran bahasa hukum dengan alur pemikiran bahasa Indonesia dengan kaidah dan tata bahasa yang berlakunya. Karena menurut penulis pemahaman bahasa hukum harus didasari oleh pemahaman akan bahasa Indonesia secara mendasar yang memuat kaidah bahasa. Dengan demikian diharapkan para pembelajar bahasa hukum dan perundangan akan mudah memahami bahasa tersebut karena telah memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kaidah bahasa Indonesia.
Menariknya buku ini adalah penggunaan contoh-contoh pemakaian bahasa Indonesia yang selama ini telah digunakan khalayak sebagai bahasa yang ‘benar” namun demikian ternyata penggunaannya tidaklah benar. Slogan Memasyarakatkan Hukum, Menghukum Masyarakat misalnya, memasyarakatkan hukum memiliki makna menjadikan masyarakat mengenal hukum atau mengenalkan hukum kepada masyarakat, namun menghukumkan masyarakat memiliki makna yang tidak masuk akal yakni menjadikan hukum itu masyarakat (hal 96). Contoh lainnya adalah penggunaan kata yang salah karena maknanya sulit dibedakan seperti kata putusan dan keputusan. Di bidang hukum dan peraturan perundangan, putusan berarti “hasil memutus”, “vonis” dan “berkaitan dengan bentuk dan maknanya dengan kata kerja memutus”. Putusan hakim berarti vonis hakim dan putusan pengadilan berarti vonis pengadilan. Keputusan berarti “hasil memutuskan” (hal 120).
Buku ini sebenarnya berupaya menjembatani keinginan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bahasa Indonesia di bidang hukum. Buku ini menurut penulis merupakan jawaban atas permasalahan yang ditemukan dalam forum-forum diskusi maupun forum ilmiah yang diikuti oleh penulis yang kemudian dirangkum. Walaupun buku ini tidak secara membahas dengan detil penggunaan bahasa hukum namun demikian buku ini setidaknya telah menjawab kebutuhan akan buku bahasa Indonesia khususnya di bidang hukum dengan pendekatan kaidah bahasanya.
Lewat buku yang tersaji ringkas ini memberi pemahaman bahwa bahasa Indonesia di bidang hukum maupun peraturan perundang-undangan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan penggunannya untuk di bidang lainnya. Selamat membaca.
#Telah dimuat di Majalah Konstitusi 2014
Oleh Nor Hidayah
Peneliti Hukum Center for Democratization Studies
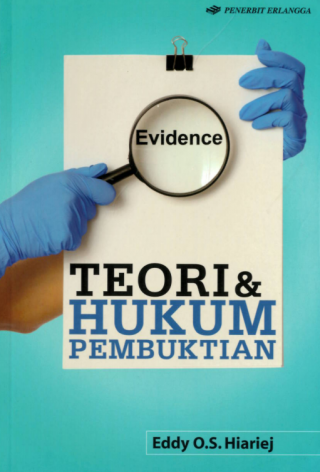
Judul Buku : Teori & Hukum Pembuktian
Penulis : Eddy O.S.Hiariej
Penerbit : Penerbit Erlangga
Tahun : 2012
Tebal : 123 halaman
Hukum pembuktian tidak akan terlepas dari ketentuan mengenai pembuktian yang terjabarkan dari alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan bukti dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan. Selain itu, hukum pembuktian juga terkait dengan kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Karenanya, hukum pembuktian sangatlah penting untuk dipahami tidak hanya formilnya tetapi juga teorinya.
Dalam buku yang ditulis oleh seorang Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada ini, kajian mengenai pembuktian dibagi menjadi enam bab yang dimulai dengan Bab pertama mengenai beberapa istilah dan arti penting tentang pembuktian. Pembahasannya dimulai dari arti bukti sendiri yang diambil dari berbagai sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia sampai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan dari beberapa tokoh hukum di Indonesia seperti R. Supomo, Sudikno Mertokusumo dan lain-lainnya mengenai pentingnya Pembuktian tersebut.
Untuk Bab Kedua mengenai Karakter dan Parameter Pembuktian yang terlebih dahulu menjelaskan hal-hal fundamental yang terkait suatu pembuktian. Selanjutnya akan membahas tentang keterkaitan akan parameter hukum pembuktian yaitu bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum. Buku ini menjabarkan tentang keenam teori tersebut yang terkait dengan parameter hukum pembuktian.
Bab Ketiga membahas tentang beberapa asas terkait dengan pembuktian, seperti due process of law. Dengan adanya asas ini tersangka mendapatkan hak-haknya. Contohnya di Amerika yang menjunjung tinggi due process of law dalam suatu kasus. Jika penyidik tidak menyampaikan terlebih dahulu hak-haknya maka tersangka dapat dibebaskan. Karenanya dikenal Miranda warnings yang berisi: “You have right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law, yao have the rights to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provide for you at government expense”. Selain itu, dalam Bab Ketiga akan dibahas pula asas presumption of innocent, legalitas, dan lain-lainnya.
Dalam Bab Keempat, tulisan akan mengurai mengenai alat-alat bukti seperti saksi, ahli, dokumen, dan real evidence atau Physical Evidence. Selanjutnya untuk Bab kelima, kita bisa mengetahui tentang pembuktian dalm perkara perdata di Indonesia, seperti bukti tulisan/bukti dengan surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah dan ahli, sedangkan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia dibahas pada Bab Keenam.
Buku ini memberikan pengetahuan komprehensif tentang pentingnya hukum pembuktian dan teori-teori yang menyertainya. Penjabaran yang diungkapkan dalam buku ini cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca yang belum mengetahui hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian. Seperti contoh, ketika umumnya kita hanya tahu tentang asas-asas yang sering didengar seperti due process of law, presumption of innocent dan legalitas, padahal ternyata masih ada beberapa asas-asas lain yang perlu dan harus kita ketahui.
Namun, masih ada beberapa kekurangan disetiap babnya yaitu kurangnya pendalaman lebih dengan penambahan contoh kasus yang pernah terjadi, sehingga para pembaca bisa lebih membayangkan atau mengacu pada hal tersebut. Selain itu, buku ini tidak melengkapi kajian mengenai hukum pembuktian di forum-forum pengadilan selain pidana dan perdata, seperti bagaimana pembuktian di Mahkamah Konstitusi misalnya. Ke depannya, penulis buku sangat diharapkan melengkapi kajian dalam buku ini khususnya terhadap teori dan hukum pembuktian dalam berbagai forum pengadilan yang spesifik. Terkait dengan itu, Prof. Eddy O.S. Hiariej sebenarnya juga pernah menulis dalam harian Kompas, 6 Agustus 2014 yang berjudul “Membuktikan Kecurangan Pilpres” yang sedikit banyak mengulas teori dan hukum pembuktian di Mahkamah Konstitusi.
#Telah dimuat di Majalah Konstitusi Agustus 2014.
Peneliti Center for Democratization Studies (CEDES), Jakarta
TANGGAL 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang Convention on the Rights of Persons with Disabilities(Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi tersebut.
Mengingat betapa pentingnya menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia pun telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 30 Maret 2007 di New York. Meski Pemerintah Indonesia belum menandatangani Optional Protocol Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tetapi Indonesia tetap memiliki komitmen untuk meratifikasi konvensi tersebut.
Akhirnya ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimunculkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dan diundangkan, 10 November 2011.
Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi konvensi tersebut. Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
Diskriminasi
Pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas secara umum telah dianggap merupakan diskriminasi. Namun, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya menyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya‘.
Mahkamah Konstitusi (MK) juga kerap menggunakan cakupan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik. Menurut penulis, diskriminasi berdasarkan disabilitas patut dimasukkan menjadi definisi formal atas diskriminasi yang diakui oleh negara.
Dengan memasukkan disabilitas menjadi bagian atas diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia Indonesia secara lebih tegas, maka upaya yang dilakukan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan lebih intensif, akan semakin kuat karena telah memiliki legitimasi hukum.
Diskriminasi Positif
Agar penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka, penyandang disabilitas pantas diberi kesempatan lebih dan prioritas untuk terlibat dalam politik, sebagaimana telah diterapkan pada persentase keterwakilan perempuan dalam politik yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Dalam pemahaman tentang konsep diskriminasi, dikenal diskriminasi positif (positive discrimination) atau yang kerap dikenal dengan pengaturan affirmative action berupa perlakuan khusus untuk mengoreksi praktik diskriminasi di masa lalu dan sekarang bagi kelompok-kelompok yang tertinggal atau termarjinalkan melalui tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak.
Hal itu dapat dibenarkan dan telah ditegaskan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.‘ Diskriminasi positif dapat dibenarkan, tetapi memang hanya bersifat temporer apabila kedudukan antarkelompok telah sama dan setara.
Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk memacu kesetaraan secarade facto tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tetapi, hal itu tidak boleh dilanggengkan karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari kesetaraan, kesempatan dan tindakan telah tercapai.
Akses
Untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas, patut dikembangkan berbagai penelitian terkait ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk tekonologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau.
Perlahan tapi pasti, bila itu dilakukan dengan dukungan semua pihak, maka akan tersedia informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya.
Khusus bagi kepentingan komunikasi dan interaksi bagi penyandang disabilitas, perlu pengaturan publik atas tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia, audio, plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, serta bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan lain.
Bagi pemerintah, hal itu dapat diterapkan pada berbagai fasilitas publik yang merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bila hal itu tersedia, maka secara tidak langsung memberi pemahaman dan kesadaran bagi warga untuk menghormati dan mendukung serta berpartisipasi penuh dan efektif dalam melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas. n
#Telah dimuat pada Jurnal Nasional, Sabtu, 17 Maret 2012.
http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-03-17/202693
oleh Nor Hidayah
Peneliti Center for Democratization Studies (Cedes)

Judul Buku: Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi
Penulis: Luthfi Widagdo Eddyono
Penerbit: Insignia Strat
Terbitan: Maret 2013
Jumlah Halaman: xiv + 164
Konsepsi negara hukum, konstitusi, dan lembaga negara saling terkait dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Negara hukum utamanya mendasarkan dirinya pada konstitusi dan tercermin dalam relasi lembaga negara dalam menyelenggarakan sistem negara yang dianutnya. Pemaknaan demikian yang coba dijelaskan dalam bab-bab awal buku ini. Selanjutnya coba diterangkan bagaimana hubungan antara negara hukum, seperti Indonesia,dengan konstitusi dan lembaga negaranya, serta upaya dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara dengan berpedoman pada UUD 1945.
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang dibahas dalam buku ini mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dipertegas dengan UU 24/2003 yang telah mengalami perubahan dengan UU 8/2011. Penjelasan Umum UU 24/2003 memberi keterangan, “Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.”
Sejak 2003 hingga 2012, terdapat 17 putusan dan 4 ketetapan untuk perkara SKLN yang telah diselesaikan oleh MK. Jika berdasarkan amarnya, putusan tersebut yakni 1 perkara (6%) dikabulkan, 3 perkara (18%) ditolak, dan 13 perkara (76%), tidak dapat diterima. Adapun untuk ketetapan, semuanya berupa penarikan kembali. Jika dibandingkan dengan perkara-perkara lain, perkara SKLN adalah perkara yang paling sedikit masuk dan diselesaikan.
Berdasarkan Laporan Tahunan MK Tahun 2012 yang dikutip dalam buku ini, sejak 2003 hingga 2012, tercatat 1.166 perkara yang telah ditangani oleh MK. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, terdapat 532 perkara (45%) Pengujian Undang-Undang (PUU), 116 perkara (10%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 497 perkara (43%) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan hanya ada 21 perkara (2%) perkara SKLN. Padahal dari berbagai pemberitaan di media, banyak sekali konflik atau potensi konflik ketatanegaraan yang terjadi dalam relasi antarlembaga negara. Apa yang mendasari sedikitnya perkara SKLN yang diselesaikan di MK? Buku ini akan menjawabnya.
Kriteria Perkara SKLN
Pada tanggal 18 Juli 2006, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Peraturan tersebut menentukan Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.
Lebih lanjut, MK dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 telah merumuskan frasa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.Untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar (objectum litis) dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan (subjectum litis). Frasa “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” juga mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi objectum litis dari SKLN oleh MK. (halaman 127). Pemahaman MK yang demikian membuat 13 perkara (76%) tidak dapat diterima. Kemungkinan sedikitnya perkara SKLN ke MK juga karena tafsiran demikian memang membatasi kandidat pemohon atau termohon.
Perlu dipahami bahwa batasan tafsiran MK sebenarnya tidak hanya pada kewenangan yang diberikan oleh UUD secara tekstual saja, tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok. Sejak Putusan Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 yang diikuti Putusan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, Mahkamah telah pula berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam sengketa kewenangan lembaga negara tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (expressis verbis) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945. Dalam hal ini, hal terpenting yang harus dinilai adalah lembaga negara yang bersengketa adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. (halaman 153).
Penulis buku ini kemudian juga menemukan bahwa penyelesaian SKLN dapat diupayakan melalui proses pengujian undang-undang, khususnya apabila ada terjadi benturan antara dua kepentingan hukum yang diatur oleh undang-undang. MK paling tidak pernah memutus tiga perkara pengujian undang-undang yang mengandung unsur sengketa antara lembaga negara, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang merupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 hakim agung; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 atas perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang sebenarnya mengandung unsur sengketa antara dua lembaga negara, yaitu KPU dan Bawaslu karena tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma, melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPU. (halaman 129).
Hukum Formil dan Materiil
Kelebihan buku ini adalah pada kelengkapan konten yang dimilikinya. Tidak hanya membicarakan norma hukum substantif yang ada dalam setiap perkara SKLN yang pernah diputus MK, buku ini juga menjelaskan secara lugas dan terperinci hukum acara yang digunakan oleh MK. Terhadap keduanya, Penulis buku juga memberikan rekomendasi, yaitu:
Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui kajian teori keberadaan MK dan SKLN, serta bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui sejakpengajuan permohonan perkara hingga putusan akhir yang dijatuhkan yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, dengan adanya ikhtisar seluruh perkara SKLN yang juga disediakan oleh Penulis menjadikan poin tersendiri bagi kita untuk dapat lebih memahami perkara-perkara SKLN yang pernah ditangani MK dan bagaimana logika penyelesaiannya. Dengan mengaji berbagai macam perkara-perkara yang telah diputus akan menambah wawasan dan keilmuan mengenai SKLN dari berbagai sudut pandang.
Dengan membaca buku ini, pembaca bisa mengetahui bagaimana penyelesaian SKLN yang merupakan cerminan utama hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Namun buku ini sepertinya memang dikhususkan bagi kajian keilmuan hukum semata karena pembaca yang kurang paham tentang hukum akan sungguh mengalami kesulitan untuk memahami setiap uraiannya. Sebagai informasi, buku ini telah pula diterbitkan dalam versi online atau e-book oleh Jaeger Publishing, Singapura. Terbitan tersebut dapat ditemukan dalam laman https://subscription4me.com/public.
#Tulisan ini telah dimuat di Majalah Konstitusi 2013.
Powered by WordPress & Theme by Anders Norén